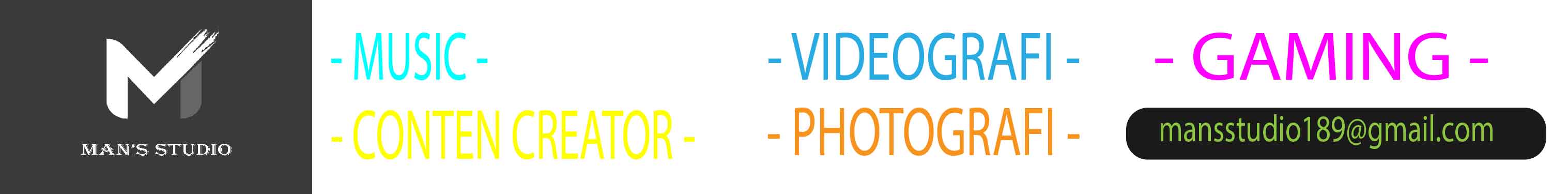Oleh : Heintje G. Mandagie / Ketua Dewan Pers Indonesia
Rasa malu, marah, dan
geram, tak terlukiskan ketika penulis menerima laporan dari seorang Pemimpin
Redaksi di Gorontalo yang merasa terusik oleh surat Dewan Pers Nomor :
346/DP-K/V/2021 perihal Pemuatan Hak Jawab. Surat Dewan Pers tersebut terkesan
memaksanya memenuhi hak jawab dari pihak pengadu Haris Suparto Tome, Kepala
Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten
Gorontalo yang sebelumnya diberitakan tertangkap basah sedang berduaan di
sebuah kamar kos bersama dengan isteri orang oleh aparat kepolisian pada sebuah
penggrebekan operasi justitia. Tak
tangung-tanggung, Dewan Pers memberi ancaman kepada Pemimpin Redaksi media
siber Butota.id menggunakan pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers agar yang bersangkutan wajib melayani hak jawab agar tidak terkena
pidana denda paling banyak 500 juta rupiah.
Kejadian ini bak mimpi
di siang bolong ketika insan pers tanah air sedang asik memperingati World
Press Freedom Day atau Hari Kebebasan Pers Sedunia. Dewan Pers justeru sibuk melayangkan surat
berbau ancaman dan pemaksaan terhadap media. Rasa malu yang dirasakan penulis
adalah ketika terduga pelaku mesum berhasil mengobok-obok kehidupan pers
nasional dan sukses memperalat Dewan Pers agar kasus yang menjeratnya semakin
kabur. Beberapa media berhasil dipaksa
membuat hak jawab dan menulis permintaan maaf secara terbuka di media
masing-masing karena takut diancam Dewan Pers. Media yang merasa tidak
melanggar kode etik dan tidak mau menuruti kemauan pengadu dan Dewan Pers pun
diancam dengan surat dari Dewan Pers.
Bagaimana mungkin
peristiwa penegakan hukum yang dilakukan aparat Kepolisian di Kabupaten
Gorontalo atas laporan warga yang menduga isterinya ditiduri oleh oknum Kepala
Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo bernama Haris Suparto Tome (pengadu) di
sebuah kamar kos, lantas diberitakan oleh berbagai media di Gorontalo, kini
menjadi bahan aduan oleh pelaku ke Dewan Pers.
Situasi yang lazim
terjadi dalam sebuah operasi penegakan hukum di Kepolisian begitu sering
diliput wartawan dari berbagai jenis media. Bahkan beberapa televisi swasta
menjadikan itu (operasi penggrebekan polisi) sebagai satu program khusus.
Tayangan yang menampilkan proses penegakan hukum seperti penggerebekan pelaku
mesum di kamar hotel, penggerebekan pelaku kejahatan premanisme, pegedar
narkoba, dan prostitusi menjadi tontonan menarik bagi masyarakat untuk
menyaksikan kinerja kepolisian terhadap penegakan hukum di negeri ini. Tidak
pernah ada pelaku kejahatan yang ditangkap basah polisi sedang berduaan di
kamar hotel lalu meminta hak jawab kepada media. Rata-rata pelaku yang digrebek
di kamar hotel malu dan menutupi wajah saat dikejar wartawan. Nyaris tidak ada
yang mau diwawancarai wartawan, termasuk kejadian yang dialami pengadu Haris
Suparto Tome saat ditangkap polisi sedang berduaan dengan isteri orang di dalam
sebuah kamar, menolak diwawancarai saat dikejar wartawan.
Anehnya, kejadian yang
diberitakan media itu dianggap Dewan Pers melanggar kode etik jurnalistik dan
tidak memenuhi hak jawab, serta mencemarkan nama baik sang pelaku atau pengadu
yakni Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo Haris Suparto Tome. Jika
penalaran dan pemahaman Dewan Pers seperti itu maka semua media yang biasa
meliput penggrebekan polisi atau operasi penegakan hukum aparat polisi akan
dianggap melanggar kode etik jurnalistik. Bagaimana mungkin fakta kejadian yang
diberitakan secara jujur dan benar itu dikategorikan melanggar kode etik jurnalistik
dan tidak memenuhi hak jawab oleh penilaian Dewan Pers. Bagi penulis, hal itu tidak masuk logika akal
sehat.
Beginilah jadinya kalau
Dewan Pers dipimpin oleh orang yang
tidak memiliki latar belakang pengalaman di bidang wartawan. Bagaimana mungkin sebuah peristiwa penegakan
hukum yang lazim diliput oleh media, kemudian pelakunya seorang pejabat kepala dinas ditangkap polisi namun Dewan
Pers mengenyampingkan fungsi sosial kontrol pers. Dari sisi moral dan etika
menjadi pejabat, itu sudah dilanggar oleh pengadu ketika ditangkap polisi
sedang berduaan dengan isteri orang. Bahkan suami dari pelaku yang ditangkap
bersama pengadu juga berharap pengadu Haris Suparto Tome dihukum sesuai
ketentuan hukum yang berlaku.
Sepertinya seluruh
anggota Dewan Pers perlu belajar lagi Undang-Undang Pers khususnya pasal 6
tentang peran pers nasional. Sangat
jelas disebutkan, Pers nasional salah satunya berperan mendorong terwujudnya
supremasi hukum, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap
hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan memperjuangkan keadilan dan
kebenaran. Bahkan untuk menjalankan peran ini, Undang-Undang Pers menyebutkan,
kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan
prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.
Jadi, jika semua pelaku
kejahatan yang ditangkap polisi lalu mengadu ke Dewan Pers karena merasa
dicemarkan nama baiknya, lalu siapa yang bertugas melakukan pegawasan dan
mendorong terwujudnya supremasi hukum? Saya ingin menanyakan hal ini kepada
seluruh anggota Dewan Pers secara terbuka dan kepada seluruh pimpinan
organisasi pers konstituen Dewan Pers. Apakah layak seorang pejabat Kepala
Dinas Kominfo yang tertangkap basah berduaan di dalam kamar bersama isteri
orang dan ditangkap polisi, melayangkan aduan tanpa harus menunggu proses di
kepolisian dinyatakan selesai dan berkekuatan hukum tetap ? Apakah fakta hukum
pengadu yang ditangkap polisi dan menjadi terlapor sebagai pelaku dugaan
kejahatan moral bersama isteri orang harus dikesampingkan oleh Dewan Pers? Bagaiman dengan penegakan
disiplin Aparatur Sipil Negara yang dilanggar oleh pengadu selaku pejabat level
kepal dinas dan menjabat Ketua Forum Kepala Dinas Kominfo se Indonesia ?
Jika hal ini tidak bisa dijawab oleh Dewan
Pers dan kroni-kroninya, maka penulis khawatir kejadian yang dialami wartawan
senior Torazidu Lahia di Riau bakal terulang lagi. Pada tahun 2017 lalu,
Torazidu Lahia menulis tentang dugaan korupsi (mantan) Bupati Bengkalis Amril
Mukminin dengan bukti fakta peristiwa pengusutan kasus korupsi itu sedang
berjalan. Namun Dewan Pers dengan lancangnya melayani aduan dari sang Bupati,
kemudian mengeluarkan rekomendasi ‘pencabut nyawa’ dan menyatakan berita yang
ditulis Torazidu Lahia bukan karya jurnalistik dan teradu tidak memiliki
sertifikat Uji Kompetensi Wartawan dan
medianya belum terverifikasi Dewan Pers. Sehingga kasus tersebut dinyatakan
bisa ditempuh di luar Undang-Undang Pers atau dengan kata lain bisa dikriminalisasi.
Akibat rekomendasi
Dewan Pers tersebut sang (mantan) Bupati kemudian benar-benar
mengkriminalisasi Torazidu dan akhirnya
dipenjara dan divonis bersalah, kemudian menjalani hukuman selama 2 tahun. Pada
waktu yang bersamaan, (mantan) Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang diberitakan
Torazidu terlibat dugaan korupsi, justeru terbukti bersalah dan didakwa sebagai
koruptor yang merugikan keuangan negara dan divonis 6 tahun penjara dan denda
500 juta Rupiah.
Saat menulis fakta
tentang nasib yang dialami Torozidu Lahia ini, hati dan persaaan penulis begitu
pedih dan miris membayangkan wartawan yang menjalankan perannya harus mendekam
di balik jeruji besi dan dinginnya lantai penjara beralaskan tikar tipis
berbalut penderitaan yang tak terkatakan. Kebebasannya terenggut oleh karena
tulisannya dipidana dan dikriminalisasi. Kemerdekaan pers sebagai salah satu
wujud kedaulatan rakyat tidak berlaku bagi Dewan Pers. Tidak ada upaya meminta
maaf kepada Torozidu Lahia pasca Bupati yang mengadu terbukti bersalah dan divonis
6 tahun penjara. Dewan Pers tidak berani mengakui kesalahannya. Kemerdekaan
pers bukan lagi wujud kedaulatan rakyat tapi wujud tirani Dewan Pers. Tidak ada
perlindungan hukum terhadap wartawan sebagaimana dijamin dalam Pasal 8
Undang-Undang Pers.
Masih jelas teringat
kematian wartawan Kemajuan Rakyat dan Sinar Pagi Baru Muhammad Jusuf dalam
tahanan karena dikriminalisasi akibat berita yang ditulisnya. Nasib yang
dialami Torozidu Lahia tak berbeda dengan apa yang dilami almarhum Muhammad
Jusuf. Keduanya menerima Rekomendasi “Pencabut Nyawa Kemerdekaan Pers” dari
Dewan Pers. Namun sayangnya Dewan Pers tidak merasa bersalah sedikitpun.
Beberapa contoh kasus
yang diurai di atas hanyalah sebagian kecil dari kasus-kasus serupa yang
membelenggu kemerdekaan pers di berbagai daerah. Telah habis kata-kata bagi
penulis untuk merangkaikan kalimat menggambarkan betapa negeri ini sudah rusak
sistem penegakan kemerdekaan persnya. Bahkan kemerdekaan pers saat ini yang
penulis rasakan lebih buruk dari era orde baru berkuasa karena ulah Dewan Pers
yang dihuni orang-orang elit yang tidak mengerti tentang permasalahan
pers.
Saat ini kondisi
kehidupan pers nasional sudah begitu memprihatinkan. Wartawan dan media
dibiarkan terlena dengan mengais rejeki dari belas kasihan nara sumber.
Wartawan dan media dibiarkan mengemis rejeki dan menjual idealisme kepada
pemerintah daerah lewat program kembanggaan Dewan Pers yakni kerja sama media
terverifikasi dengan pemda.
Media yang belum
terverifikasi dicap media abal-abal. Dan wartawan yang belum mengikuti Uji
Kompetensi Wartawan atau UKW (ilegal dan abal-abal) malah selama ini dipotret
atau dicitrakan sebagai wartawan abal-abal.
Tapi semua wartawan hanya diam membisu, pasrah pada keadaan.
Ketika disentuh sedikit
dengan fasilitas wadah penyaluran unek-unek lewat Musyawarah Besar Pers
Indonesia 2018 dan Kongres Pers Indonesia 2019 rinuan wartawan pun bergerak dan
meledak-ledak namun surut seketika bak ditelan bumi. Wartawan dan media yang
belum terjangkau Dewan Pers pun nyatanya tetap diam membisu karena takut
dikriminalisasi dan dihambat akses ekonominya. Sebagian besar pasrah dan
terlena.
Bahkan kelompok
organisasi pers konstituen Dewan Pers pun tak menyadari bahwa sesungguhnya
mereka merupakan bagian dari korban pembiaran Dewan Pers terkait hak untuk
mendapatkan kesejahteraan melalui perusahaan pers tempatnya bekerja. Sudah
menjadi rahasia umum wartawan media mainstream hampir 90 persen masih menerima
imbalan jasa pemberitaan dari nara sumber untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
Jangan ada dusta di
antara kita. Karena penulis pernah menjadi bagian dari wartawan media
mainstream yang justeru menyaksikan praktek menerima amplop lebih parah
dilakukan wartawan media mainstream ketimbang wartawan media mingguan atau
bulanan dan media lokal non mainstream. Hampir sebagian besar wartawan pos
liputan di gedung pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten masih menerima
imbalan secara diam-diam karena jasa pemberitaan.
Gaji wartawan media
mainstream berskala nasional pun masih jauh dari kata sejahtera. Berdasarkan
riset yang dilakukan DPP SPRI, wartawan media mainstream berskala nasional
selayaknya digaji minimal 25 juta rupiah per bulan untuk level reporter dan
gaji minimal 100 juta rupiah untuk wartawan level pemimpin redaksi agar terjamin
independensinya. Angka yang disebutkan tadi masih tergolong kecil dibanding
raihan pendapatan belanja iklan tahunan yang diperoleh media-media mainstream
berskala nasional yang mencapai belasan bahkan puluhan triliuan rupiah per
tahun.
Tingkat kesejahteraan
dan pendapatan perusahaan pers dari tahun ke tahun nyaris tidak mengalami
penurunan. Malah sebaliknya belanja iklan nasional terus meningkat setiap
tahunnya dan berpengaruh pada meningkatnya pendapatan media dari perolehan
belanja iklan nasional tersebut.
Lantas apa peran Dewan
Pers. Sama sekali tidak ada dalam upaya meningkatkan kehidupan pers nasional.
Dewan Pers hanya sibuk mengurusi kerja sama media terverifikasi dengan
pemerintah daerah. Dewan Pers sibuk mengarahkan media untuk menjual idealisme
dan independensi media kepada pemerintah daerah lewat kerja sama publikasi dan
sosialaisasi media.
Apakah perlu pemikiran penulis ini kembali terbukti di
kemudian hari namun diklaim oleh Dewan Pers. Sama halnya ketika penulis sejak
tahun 2018 sampai tahun 2021 menulis kritikan terhadap pelaksanaan UKW
abal-abal dan ilegal yang dilakukan Dewan Pers. Tadinya Dewan Pers bersih kukuh
UKW yang dilakukannya adalah profesional dan sesuai dengan Undang-Undang yang
berlaku.
Namun di pertengahan
April 2021, Dewan Pers dikejutkan dengan fakta hukum bahwa Badan Nasional
Sertifikasi Profesi atau BNSP mengegaskan bahwa Dewan Pers boleh melaksanakan
sertifikasi kompetensi tapi tidak boleh secara langsung, karena harus melalui
Lembaga Sertifikasi Profesi yang berlisensi BNSP. Sontak publik pers terbuka
mata lebar-lebar bahwa praktek UKW Dewan Pers selama ini ternyata abal-abal dan
melaggar hukum.
Tiba-tiba Dewan Pers
mendatangi BNSP dan ‘mengemis’ peran dengan menggiring opini bahwa Rekomendasi
Dewan Pers diwajibkan bagi LSP dalam mendapatkan lisensi di BNSP. Kenegarawanan
Muh Nuh diuji dalam peristiwa hukum ini. Penulis yang merupakan Ketua Umum SPRI yang selama ini getol menulis kritikan
tentang UKW Dewan Pers yang cacat hukum, sering dipotret abal-abal namun justeru
berhasil membuktikan kritikannya benar dengan mendirikan LSP dan menyusun
standar kompetesi wartawan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Standar Kompetesi
Wartawan yang digunakan Dewan Pers selama ini adalah abal-abal dan tidak
memenuhi ketentuan KKNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
203 tentang Ketengakerjaan dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
SPRI menjawab semua itu dengan menyusun Standar Kompetensi Kerja Khusus
Wartawan berbasis KKNI yang teregistrasi di Dirjen Binalatas Kemanker RI.
Fakta ini apakah akan
berulang ketika penulis dan kelompok yang tergabung dalam Dewan Pers Indonesia
kembali membuat gebrakan memperjuangkan pendapatan media atau perusahaan pers
melalui program pembentukan peraturan daerah di seluruh Indonesia tentang
belanja iklan nasional menjadi belanja iklan daerah. Penulis berharap program ini
tidak dilawan oleh Dewan Pers tapi didukung untuk bersama-sama, selayaknya
praktek UKW lewat jalur BNSP, mendorong
pemerintah membuat perda tentang belaja iklan daerah sebagai potensi income
bagi perusahaan media.
Dengan cara ini jika
media telah berhasil meraih pendapatan besar dari belanja iklan daerah maka
tidak perlu lagi ada kerja sama media dengan pemerintah daerah dengan sumber
pembiayaan dari APBD karena sosialisasi kegiatan pemerintah itu sudah merupakan
tanggung-jawab dan peran media sebagai alat sosial kontrol.
Penulis berharap, ke
depan nanti tidak ada lagi perbedaan atau dikotomi antara konstituen dan non
konstituen. Karena bagi penulis, tidak lah penting bagi Dewan Pers atau Dewan Pers Indonesia
gontok-gontokan atau kubu-kubuan namun pada prakteknya semua akan menuju satu
titik yaitu upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan
pers nasional ke arah yang lebih baik dan sejahtera.
Penyatuan sertifikasi
kompetensi wartawan melalui BNSP seharusnya menjadi starting poin bagi insan
pers tanah air untuk menyatu dalam satu visi membawa kehidupan pers nasional
yang sejahtera dan merdeka.
Seandainya, Dewan Pers
melihat bahwa wartawan, pemilik dan pengelola perusahaan pers, pengurus
organisasi pers di luar konstituen Dewan Pers adalah sesama anak bangsa yang
berhak mendapat perlakuan yang sama dan berhak mendapatkan perlindungan hukum,
dan perlu mendapat pembinaan, dan tidak dilihat sebagai musuh atau sampah
masyarakat, tapi sebagai insan pers Indonesia, maka sikap kenegarawanan Muhamad
Nuh selaku Ketua Dewan Pers perlu diuji dalam hal ini.
Penulis yang dipilih
sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia pun tidak akan merasa malu dan ragu mengakui keberdaaan Dewan Pers jika pengurus
Dewan Pers mau memperbaiki cara pandang dan kembali ke cita-cita para pejuang
pers di era reformasi lalu. Apalah arti Dewan Pers Indonesia jika pada
prakteknya masih banyak wartawan dan media yang termarjinalkan karena
berlawanan terus dengan kebijakan Dewan Pers. Ego sektoral perlu dilepas.
Asalkan pers bisa sejahtera. Jika pers Indonesia bersatu maka kemerdekaan pers
yang sesungguhnya adalah kesejahteraan pers itu sendiri. Sebebas apapun
kemerdekaan pers di Indonesia jika wartawan dan media tidak sejahtera maka itu sama saja pembohongan publik. Titik perjuangan kita saat ini adalah
melawan konglomerasi media. Mari kita ajak Dewan Pers membuka mata dan bersatu
melawan monopoli belanja iklan nasional.
Beranikah Dewan Pers memperjuangkan kesejahteraan pers dengan mendorong
pemerintah membuat peraturan agar belanja iklan bisa terdistribusi ke daerah?
Kita tunggu saja. Jangan sampai ketika Dewan Pers Indonesia bergerak dan
berhasil, Dewan Pers malah sibuk mengambil alih peran tersebut meski terkadang
nyaris terlambat. *