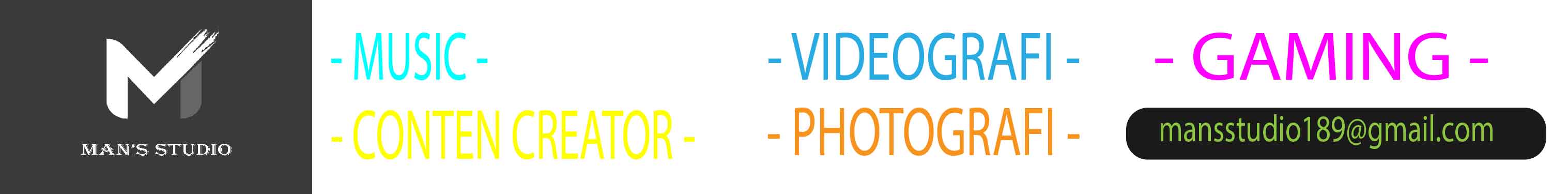|
| Foto : Ajimuddin el Kayani Aktivis Sumenep, Madura (Istimewa) |
lpktrankonmasi.com, Surabaya - Nasionalisme kali ini akan kita fokuskan ke dalam makna khusus yang terlihat sempit namun luas jangkauannya yakni cinta tanah air. Sebuah rasa suka, bangga dan bahagia dengan tanah kelahiran, tanah tumpah darah kita. Tempat di mana kita dilahirkan, hidup dan menjalani masa kanak-kanak hingga orang tua kita berkenan melepas kita untuk merantau atau pergi ke daerah lain. Cinta kampung halaman selalu fenomenal ketika lebaran Ramadhan menjelang dalam setiap tahunnya. Cinta tanah air ini juga tidak hanya dialami oleh orang biasa tetapi juga pernah diungkapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW atas kerinduannya kepada kota Makkah saat baginda hijrah dan berada di Madinah. “Tidak ada negeri yang lebih baik dan paling aku cintai daripada kamu (Makkah), kalaulah sekiranya kaumku tidak memaksaku untuk keluar dari sini tentu aku tidak akan tinggal di tempat lain. HR. al-Tirmidzi no 2926.
Cinta tanah air memiliki banyak ekspresi yang salah satunya ditampilkan dengan tradisi pulang kampung (silaturrahim ke kampung halaman). Tradisi ini telah mendarah-daging di Indonesia, bahkan menurut Silverio Raden Lilik Aji Sampurno (dosen sejarah Sanata Dharma) kebiasaan ini sudah ada sejak era Majapahit dahulu kala. Negara yang besar telah menempatkan beberapa petingginya untuk mengurus wilayah di luar ibu kota yang mana dalam kurun tertentu atau setiap tahun harus menghadap raja dan pulang kampung halaman. Maka dari perspektif ini, baik secara agama maupun secara social, kebiasaan pulang kampung bukan termasuk perbuatan bid’ah.
Tentu banyak sekali narasi dan analisa terkait rasionalitas pulang kampung, namun dalam hal ini kita lebih membaca di ranah kefitrahan kita sebagai manusia sejarah. Pulang kampung adalah naluri kesejarahan yang memiliki potensi besar untuk kembali ke pengaturan awal atau napak tilas dan merenungkan ulang bawa daging dalam tubuh kita pernah bersumber dari makanan yang diantaranya dikasih oleh sanak family warga kampung halaman juga untuk mengenali diri sendiri, asal-uslul dan siapa diri kita sebenarnya. Kehidupan urban pastilah mendatangkan sekian polusi peradaban yang mencerabut akar budaya dan sosiologis kita bahkan telah mencetak kita menjadi manusia A-historis. Tidak punya nalar sejarah dan seolah begitu saja ada dan menjadi kuat. Dan hanya dengan pulang kampunglah dimungkin dapat menemukan kembali diri kita yang hilang dan tergerus oleh problematika kehidupan di rauntau.
Pulang kampung merupakan restorasi diri seorang manusia sebagai makhluk sosial. Ketika keadaban awal di kampung halaman pernah terkoyak karena adanya benturan dengan kebudayaan rantau, maka ia perlu menenangkan diri, mencerap kembali aroma kearifan kampung halaman. Pulang kampung atau mudik adalah fenomena psikologis yang menurut Emha Ainun Najib, adalah tanda bahwa mereka sedang setia kepada tuntunan sukmanya untuk bertemu dan berakrab-akrab kembali dengan asal-usulnya. Mudik adalah realisasi dari komitmen batin manusia terhadap sangkan paran dirinya (Sedang Tuhanpun Cemburu : 1994).
Meskipun bagi Umar Kayam, mudik tidak lebih dari sekedar peristiwa budaya (Seni, Tradisi dan Masyarakat : 1981) namun hal itu digerakkan oleh rasa cinta atas tanah kelahiran di mana seseorang untuk pertama kalinya dihidupkan, melihat alam dan mengenal kehidupan. Dan rasa cinta itu naluriah, alami dan nyaris menjadi kesadaran kolektif masyarakat Indonesia. Bagaimanapun seseorang telah menemukan hidupan dan memiliki kehidupan di tanah rantau, ia masih tidak akan pernah menghilangkan realitas awal dirinya ada yaitu tanah tumpah darahnya. Mereka tetap ingin melestarikan daerah asal sebagai sebuah entitas kehidupan yang mewariskan kehormatan,
Mudik dengan demikian merupakan naluri luhur untuk sebuah cinta tanah air yang dalam terminology kenegaraan lebih dikenal sebagai nasionalisme. Dan Indonesia ditopang oleh sekian nasionalisme lokal atau kecintaan atas kampung halaman yang direferesentasikan dalam budaya mudik ini. Nasionalisme skala kecil ini semakin kokoh membangun NKRI karena sesungguhnya telah demikian lama mengalami akulturasi etnikal. Sebuah proses percampuran anggota masyarakat antara etnis satu ke dalam etnis lainnya dengan saling menghargai dan tidak saling meniadakan.
Jika napak tilas atau mudik ini terkendala oleh musibah pandemi covid-19, apakah mudik virtual dapat menjadi gantinya? Tentu saja tidak, tetapi mungkin saja dapat mengurangi rasa rindu terutama bagi mereka yang jarang sekali silaturrahim on line dengan sanak saudara di kampung. Namun sebagai bentuk upaya keselematan semua pihak, tidak boleh tidak, harus kita patuhi bersama. Meskipun dalam mudik virtual ini belum sepenuhnya supporting untuk menampung muatan psikologi cinta tanah kelahiran. Sebab jaringan internet belum rata menjangkau pelosok tanah air kita, belum lagi persoalan sibuknya lalu lintas dunia maya ketika semua orang berselancar di jalur tersebut.
Bagaimana realiasasi sungkem kepada orang tua lewat media android? Secara simbolik tentu saja bisa beragam model, akan tetapi tidak akan bisa merasakan sentuhan tangan ibu-bapak ke pundak dan kepala kita sebagaimana ketika mudik lokal. Dalam istilah Michel Foucault (filsuf) pastilah ada patahan episteme dalam model mudik virtual dimaksud karena tidak terpenuhinya totalitas sambung batin. Sentuhan magis yang merefresh alam batin, sulit dicapai melalui kanal virtual. terlebih bagi kita, masyarakat Indonesia yang masih mengkolaborasikan tiga jenis alam fikir sekaligus yaitu alam fikir teologis, metafisik dan alam fikir positifistik. Tidak sah (ada yang hilang) rasanya jika wujud belum bertemu wujud.
Namun kita sepakat bahwa dalam kondisi rumit seperti sekarang ini tidak akan mengurangi rasa hormat kita kepada kampung halaman dan keluarga di sana. Terkendalanya nasionalisme lokal ini, juga tidak akan melunturkan perspektif nasionalisme besar kita yaitu NKRI, karena bagaimanapun nasionalisme juga bagian penting dari iman dan cara keberagamaan kita. InsyAllah banyak yang menang dalam perang melawan hawa nafsu di bulan Ramadhan ini, dan harapannya, kita juga mampu menang dalam merawat kebhinnekaan dan nasionalisme kita untuk tanah tumpah darah tempat kita makan, minum dan hidup ini, walaupun tanpa mudik. (Penulis: Ajimuddin)